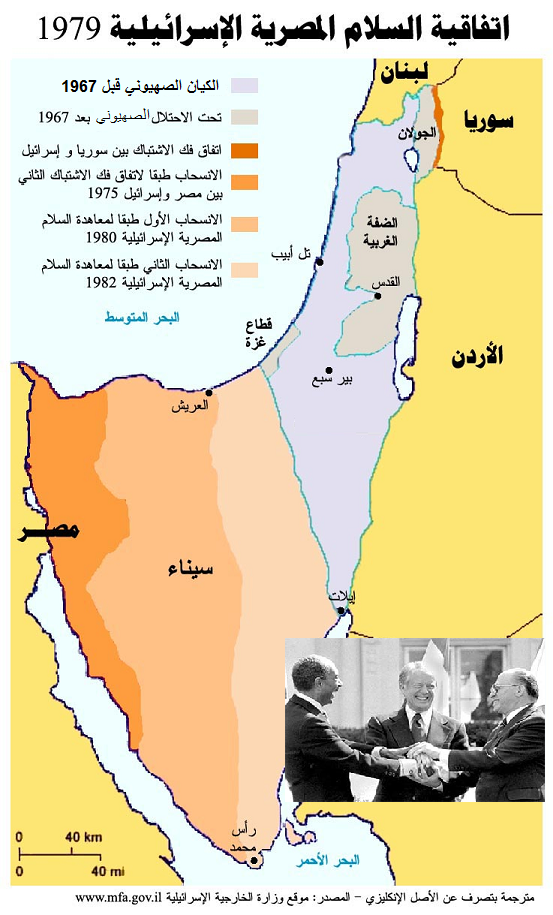Sabra adalah nama dari sebuah pemukiman miskin orang Lebanon di pinggiran selatan ibukota Beirut, yang bersebelahan dengan kamp pengungsi UNRWA di Shatila, dibangun untuk para pengungsi Palestina pada tahun 1949. Selama bertahun-tahun penduduk dari kedua wilayah tersebut menjadi semakin bercampur, sehingga istilah “kamp Sabra dan Shatila” menjadi akrab di telinga masyarakat.
Shatila merupakan nama dari sang pemilik tanah yang menyumbangkan tanahnya untuk para pengungsi Palestina korban tragedi Nakba pada tahun 1948. Pemilik tanah itu bernama Sa’dudin Basha Shatila, salah seorang warga di Lebanon. Sehingga sejak saat itu, kamp pengungsian Palestina di lokasi tersebut dikenal dengan nama Shatila.
Latar Belakang Tragedi Shabra Satila
Semenjak tahun 1975 kondisi Lebanon tidak kondusif. Beberapa kali terjadi kerusuhan dan pembunuhan yang menyebabkan meletusnya perang saudara. Kondisi ini berlangsung hingga tahun 1982 yang pucaknya adalah terbunuhnya presiden Lebanon, Bashir Gemayel yang juga pimpinan tertinggi kelompok Phalange, milisi bersenjata Kristen Maronit. Peristiwa ini menyulut kemarahan kubu Phalange dan dimanfaatkan oleh israel untuk mengakambinghitamkan PLO ( Pejuang Palestina ) sebagai pihak yang bertanggungjawab terhadap tewasnya Gemayel.
Setelah israel berhasil memprovokasi kelompok Phalange, akhirnya mereka ingin melakukan aksi balas dendam dengan cara menangkap dan membunuh anggota PLO yang dikabari israel bersembunyi di kamp pengungsian Sabra Shatila. Pembalasan akhirnya benar mereka lakukan dengan membantai warga Palestina yang mendiami Sabra Shatila. Pembantaian ini terjadi pada tanggal 16 September 1982 yang dilancarkan oleh milisi Phalange dengan bantuan tentara israel. Mereka yang bertanggungjawab dalam aksi ini adalah Menteri Perang israel, Ariel Sharon dan panglima israel Rafael Eitan dibantu oleh kelompok Kristen Phalange di bawah komando Elie Hobeika.
Pembantaian dimulai sekitar pukul 17.00 waktu setempat, pada hari Kamis, 16 September 1982. Sekitar 600 milisi Phalange memasuki kamp Shatila. Orang-orang bersenjata itu mulai memasuki rumah-rumah para penduduk, kemudian memberondong penghuninya secara membabi buta. Maka terdengarlah suara rentetan tembakan di setiap sudut kamp, raungan, jeritan serta tangisan dari para korban.
Para pelaku bengis itu pun tak segan memukulkan kampak ke arah para orang tua, wanita dan anak-anak, sementara sisanya mereka tembaki tanpa pandang bulu. Mereka merobek perut wanita hamil dan mengambil janinnya untuk kemudia mereka habisi nyawanya. Mereka juga memburu anak-anak laki dan memperkosa massal para gadis sebelum kemudian mereka bunuh.
Masih banyak kisah menyayat hati lainnya dari tragedi berdarah di Sabra Shatila yang tentu semuanya tidak bisa penulis utarakan di sini. Namun yang tak kalah menyedihkan adalah sikap dari dunia internasional, yang hanya mampu mengecam tanpa memiliki kemampuan untuk menyeret Ariel Sharon selaku otak pembantian tersebut ke Mahkamah Kriminal Internasional.
Ariel Sharon pada tahun 2001 justru diangkat menjadi Perdana Menteri israel, tentu ini ibarat pelecehan terhadap hukum, seakan ia ingin mengatakan dirinya kebal terhadap hukum, terutama dari tuduhan sebagai dalang pembantaian di kamp Sabra Shatila.
Hingga saat ini para korban dari tragedi Sabra Shatila masih menuntut keadilan. Keadaan mereka di kamp pengungsian pun semakin hari semakin memburuk, karena kebijakan pemerintah Lebanon yang kerap mengucilkan keberadaan para pengungsi Palestina di sana. UNRWA selaku organisasi PBB yang menangani permasalahan pengungsi Palestina keuangannya juga terus mengalami difisit, sehingga menghambat program-program yang selama ini telah berjalan. Tentu buruknya kondisi para pengungsi itu menjadi PR kita bersama, untuk mengembalikan mereka hidup layak dan merdeka, hingga saatnya nanti kembali ke tanah air yang selama ini mereka rindukan. Wallâhul Musta’ân.
Saiful Bahri, Lc.